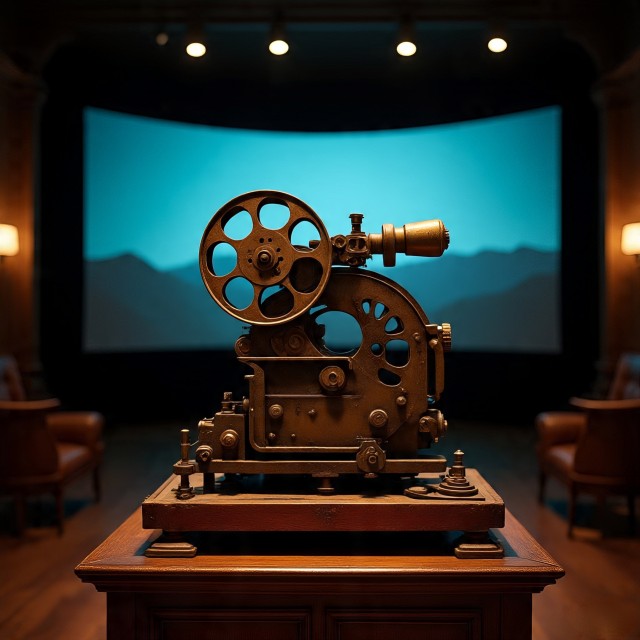Urbannews | Setiap film yang diputar di ruang festival bagaikan lembar kehidupan yang dibuka. Para juri Festival Film Wartawan (FFW) yang berjibaku beberapa bulan terakhir ini, tak sekadar menilai tata kamera, skenario, atau akting, tetapi juga menelisik bagaimana film itu merekam denyut sosial dan wajah budaya bangsa. Bukan pula sekadar ajang apresiasi karya sinema, melainkan ruang tafsir atau dialektika di mana film dibaca sebagai cermin kehidupan.
Di balik layar, para juri menimbang film dengan kepekaan sosial budaya yang mereka bawa, tak hanya menilai keindahan teknis layar lebar, tetapi juga membaca bagaimana sebuah sinema bicara kepada masyarakat—tentang identitas, keresahan, hingga harapan. Di balik meja penjurian, setiap film yang diputar menjelma seperti naskah kehidupan.
Para juri Festival Film Wartawan mengupasnya dengan tatapan yang tajam, namun tetap dilapisi rasa. Mereka tidak hanya bertanya: apakah film ini indah? Melainkan juga: apa yang dituturkan film ini tentang manusia, tentang bangsa, tentang kebudayaan yang sedang berubah?
Di ruang penjurian, sinema diperlakukan sebagai dialektika antara estetika dan etika. Setiap keputusan bukan hanya penilaian teknis, melainkan pernyataan: bahwa film Indonesia seharusnya tetap berpijak pada realitas sosial budaya, agar pesan yang lahir tidak kehilangan nyawa.
Di ruang penjurian itu, layar lebar seakan bergeser menjadi cermin raksasa. Para juri membaca bagaimana film mampu memantik kesadaran, menyentuh nalar publik, atau justru menantang norma yang mapan. Mereka tahu, film bukan sekadar hiburan, melainkan dialektika—antara estetika dan etika, antara seni dan kehidupan.
Film dipandang sebagai artefak sosial—rekaman zaman yang merekam denyut kota, bisik desa, atau keresahan generasi muda yang gelisah. Setiap adegan dianalisis bukan hanya dari sinematografi atau alur cerita, tetapi juga resonansinya pada realitas sosial. Nilai budaya, cara pandang masyarakat, hingga simbol-simbol kecil yang melekat dalam dialog menjadi bahan perenungan.
Maka, keputusan yang lahir bukan semata angka atau penghargaan, melainkan penegasan bahwa sinema Indonesia harus terus berpijak pada realitas sosial budaya yang hidup di masyarakatnya. Karena di situlah kekuatan film: ia menjadi bahasa universal yang mampu merangkai empati, kritik, dan harapan.